7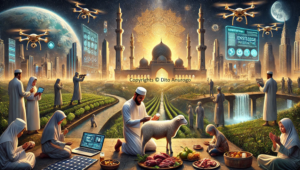
Malam merambat pelan di langit Nusantara, sementara gema takbir mengalun dari surau-surau kampung hingga masjid-masjid raya di jantung kota metropolitan. Idul Adha datang lagi. Hari besar yang tak hanya menjadi perayaan keagamaan umat Islam, namun juga momen spiritual, sosial, dan kultural yang sarat makna. Ia seperti cermin raksasa yang mengajak bangsa ini menatap dirinya sendiri—mengenang Ibrahim, merenungi Ismail, dan memaknai ulang pengorbanan.
Dalam sunyi yang kudus, seekor domba digiring menuju tempat penyembelihan. Di balik ritual yang tampak sederhana itu, tersembunyi lapisan-lapisan filosofi yang tebal dan dalam. Idul Adha bukan sekadar hari menyembelih hewan kurban. Ia adalah liturgi kepatuhan, simbol totalitas cinta kepada Tuhan, sekaligus pernyataan tegas tentang pentingnya relasi sosial yang adil dan berempati. Dalam satu tarikan napas, ia adalah momen sakral dan sekaligus praksis sosial.
Indonesia yang menatap usia emasnya di 2045, seratus tahun setelah proklamasi kemerdekaan, memerlukan semangat seperti itu. Sebuah energi kolektif yang menyatu antara nilai spiritualitas tinggi dengan komitmen sosial dan kebangsaan. Seperti Ibrahim yang meninggalkan tanah kelahirannya, Indonesia pun harus berani meninggalkan zona nyaman, menanggalkan egoisme sektoral, dan menghadapi masa depan dengan keberanian moral yang kokoh.
Idul Adha mengajarkan kita tentang ikhlas, bukan sebagai kata manis dalam khutbah, tapi sebagai keniscayaan dalam pembangunan. Ikhlas (al-ikhlāṣ) dalam bahasa Arab berasal dari akar kata kh-l-ṣ yang berarti memurnikan. Maka, ikhlas dalam konteks kebangsaan berarti memurnikan niat bernegara dari kontaminasi kepentingan pribadi, korupsi kekuasaan, dan oportunisme politik. Menuju Indonesia jaya 2045, kita butuh pemimpin dan rakyat yang mampu berkurban bukan hanya harta, tapi juga ambisi dan kenyamanan demi maslahat publik.
Jika kita menarik benang merah Idul Adha ke dalam ranah biopolitik—konsep yang dikembangkan oleh Michel Foucault—maka pengelolaan populasi bukan sekadar soal statistik dan angka, tapi tentang bagaimana negara mengelola kehidupan secara etis dan bermartabat. Dalam konteks ini, daging kurban bukan sekadar pangan, tapi simbol distribusi keadilan. Bayangkan jika semangat distribusi itu menular ke seluruh aspek ekonomi: tanah, pendidikan, akses kesehatan, dan teknologi. Maka Idul Adha menjadi simulakra (representasi yang menyerupai tapi lebih kuat dari realitas) dari masyarakat adil yang ingin dicapai Indonesia pada 2045.
Bangsa ini akan menghadapi tantangan multidimensi: revolusi industri berbasis AI dan nanoteknologi, perubahan iklim, krisis air dan pangan, serta gejolak geopolitik kawasan. Namun seperti Ibrahim, kita diajak untuk tidak gentar. Takdir peradaban bukan ditentukan oleh besarnya tantangan, tapi oleh kesanggupan moral untuk menjawabnya dengan keteguhan.
Teknologi canggih seperti CRISPR dalam biologi molekuler telah memungkinkan manipulasi genetik yang luar biasa. Stem cells menjanjikan regenerasi jaringan yang dulu mustahil. Namun di tengah kemajuan itu, kita diingatkan untuk menyeimbangkan antara eksplorasi ilmiah dan etika spiritual. Dalam Islam, ilmu adalah amanah. Maka keilmuan tanpa adab adalah laksana pisau di tangan anak kecil: tajam, tapi membahayakan.
Idul Adha, dalam tafsir sufistik, adalah titik puncak fanā’—lenyapnya ego dalam ketuhanan. Ini sejatinya adalah kritik terhadap antroposentrisme (pusatnya segala sesuatu pada manusia). Sebuah kritik yang relevan ketika manusia modern begitu pongah dengan sains namun rapuh dalam nurani. Saat bumi terluka karena kerakusan industrialisasi, kurban menjadi pengingat bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan. Maka Indonesia 2045 haruslah Indonesia yang ekologis, bukan sekadar ekonomis.
Kita juga tak bisa melewatkan makna hermeneutik dari kisah Ibrahim. Ia bukan sekadar membaca perintah Tuhan secara literal, tapi juga menafsirkan secara eksistensial. Bahwa ketaatan tak selalu lurus dan tanpa tanya. Justru dalam tanya itulah tumbuh kedalaman iman. Maka generasi muda Indonesia harus diajak berpikir kritis. Bukan sekadar ikut arus, tapi mampu membaca realitas, menafsirkan sejarah, dan menyusun masa depan dengan nalar dan nurani.
Bangsa besar lahir dari budaya literasi. Para ulama dahulu adalah ilmuwan, filosof, dan penyair sekaligus. Seperti Ibn Sina yang menulis tentang kedokteran dan metafisika, atau Al-Ghazali yang merangkai tasawuf dan logika. Maka Indonesia 2045 tidak cukup hanya mencetak insinyur dan pebisnis, tapi juga pemikir dan penyair, ahli hadis yang juga paham imunologi, qari yang juga insinyur nanoteknologi. Karena masa depan bukan milik spesialisasi sempit, tapi integrasi ilmu.
Dalam konteks kebangsaan, kurban adalah pesan yang sangat politis. Bahwa kekuasaan bukan untuk dinikmati, tapi dikurbankan demi kepentingan rakyat. Maka dalam Idul Adha, pemimpin mestinya merenungi makna itu. Bahwa jabatan adalah amanah, bukan privilese. Bahwa istana adalah tempat berkurban, bukan menimbun. Maka Indonesia 2045 adalah Indonesia yang berhasil membangun sistem politik beretika, bukan hanya demokratis secara prosedural.
Melalui perspektif fiqh sosial yang dikembangkan oleh KH. Ali Yafie atau bahkan maqāṣid al-sharī‘ah (tujuan-tujuan utama syariat) ala al-Syatibi, kurban bukan semata soal sah atau tidaknya penyembelihan, tapi soal nilai: keadilan, kasih sayang, keberlanjutan. Artinya, fikih tidak bisa terus-menerus berkutat pada literalitas, tapi harus melompat ke arah kontekstualitas. Ini menjadi tantangan besar bagi pendidikan Islam: membumikan teks, memanusiakan hukum.
Budaya Idul Adha juga adalah ruang pertunjukan sosial. Orang kaya menyerahkan hewan kurban, lalu dagingnya didistribusikan ke masyarakat bawah. Ini adalah demokratisasi daging—mungkin satu-satunya momen dalam setahun ketika seorang buruh tani bisa membawa pulang daging kambing. Maka jangan pernah kita anggap remeh momentum ini. Ia adalah pelajaran tentang kesetaraan yang paling sederhana tapi membekas.
Kalau ditarik dalam diskursus geopolitik, maka kurban adalah bentuk resistensi terhadap sistem global yang timpang. Ketika negara-negara kaya menimbun vaksin saat pandemi, kita diingatkan bahwa solidaritas global hanya utopia jika tak dibarengi kesediaan berkurban. Maka Indonesia harus membangun diplomasi berbasis nilai—menjadi jembatan antara Utara dan Selatan, Islam dan Barat, ilmu dan spiritualitas.
Adapun dari sudut pandang filsafat eksistensial, Idul Adha adalah panggilan untuk melampaui dirinya. Kierkegaard menyebut momen Abraham sebagai “teleological suspension of the ethical”—ketika nilai etis ditangguhkan demi nilai iman. Tapi Islam tak pernah menjadikan iman sebagai alasan meninggalkan etika. Justru dalam Islam, iman dan etika adalah satu. Maka bangsa ini pun harus melampaui pragmatisme politik demi cita-cita luhur yang transenden.
Dalam semangat filologis, kita bisa membaca ulang teks-teks klasik tentang kurban dan memaknainya ulang dalam konteks Indonesia kontemporer. Tafsir bukan sekadar membaca kitab, tapi membaca realitas. Maka guru ngaji yang paham semiotika dan dosen filsafat yang hafal al-Quran bukanlah anomali, tapi keniscayaan. Karena masa depan tidak bisa dibangun hanya dengan hafalan, tapi dengan pemahaman.
Kurban dalam Idul Adha adalah sebuah bahasa universal. Sebuah narasi yang melintasi batas-batas etnis, kelas, dan geografi. Maka sangat tepat jika hari ini kita menjadikan Idul Adha sebagai titik berangkat menuju Indonesia jaya 2045. Sebuah Indonesia yang tidak hanya besar secara ekonomi, tapi agung secara nilai. Yang tak hanya kuat secara teknologi, tapi luhur secara moral. Yang tidak hanya ramai oleh infrastruktur, tapi tenang dalam jiwa rakyatnya.
Malam masih terus merambat. Takbir belum selesai. Tapi di hati jutaan orang Indonesia, ada doa yang sama: semoga bangsa ini kuat seperti Ibrahim, ikhlas seperti Ismail, dan jaya karena mampu berkurban bukan hanya di altar agama, tapi juga di altar kemanusiaan. (Dokter Dito Anurogo MSc PhD, alumnus PhD dari IPCTRM TMU Taiwan, dosen FKIK Unismuh Makassar, peneliti di Institut Molekul Indonesia, penulis-trainer profesional berlisensi BNSP, reviewer puluhan jurnal internasional-nasional)
